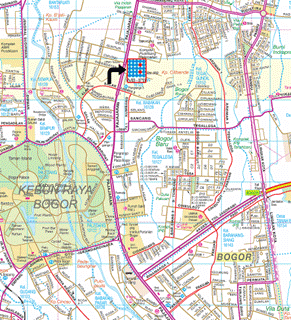
Pendahuluan
Kegiatan di alam bebas kini semakin pesat berkembang di kalangan masyarakat, terutama para pecinta alam yang sering kali menjelajahi daerah-daerah perawan dan sulit untuk dijangkau. Kegiatan penjelajahan medan seperti mendaki gunung, hiking, arung jeram, caving, menjelajah rimba dan rawa, serta kegiatan di alam bebas lainnya, tentunya memerlukan persiapan yang cukup matang. Tanpa persiapan yang matang akan dapat menimbulkan kesulitan dan bahkan kadang membahayakan dan berakibat pada hal yang fatal. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan di alam bebas tersebut, pengetahuan dan ketrampilan membaca peta kompas dan orientasi medan mutlak dikuasai. Apabila seorang anggota Search And Rescue (SAR) yang tugasnya mencari dan menolong korban. Kegunaan peta dan kompas sangat besar sekali dalam mengenal keadaan medan yang akan dijelajahi, dapat merencanakan lintasan yang akan dihadapi, merencanakan peralatan dan makanan yang dibutuhkan, serta untuk memperkirakan kedudukan atau loasi medan.
Pengertian Navigasi Darat
adalah salah satu ilmu pendukung yang harus dikuasai oleh seorang petualang ataupun penjelajah yang baik. Navigasi berasal dari bahasa Yunani, Navis yang berarti kapal atau perahu sedang Agesi berarti mengarahkan. Jadi navigasi adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara untuk menentukan atau mengarahkan suatu perjalanan atau misi dari suatu titik awal pemberangkatan ke titik tujuan segala macam keadaan cuaca dengan aman dan seefisien mungkin.
adalah sebagian dari ilmu navigasi yang dalam prakteknya selalu menggunakan seperangkat alat bantu yakni peta, kompas, sehingga Navigasi darat diistilahkan dengan ilmu medan peta kompas. Penjelasan mengenai peta kompas meliputi pengertian peta topografi, kompas dan teknik peta kompas
Peta
Pengertian Peta
Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti kenampakan sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan digambar pada bidang datar melalui system proyeksi tertentu. Dalam dunia kartografi, sering disebutkan bahwa sebuah peta lebih berharga dari seribu bahasa. Artinya bahwa sebuah peta dapat menyajikan banyak sekali informasi. Pada uraian ini kita memakai peta topografi? Karena peta topografi menggambarkan sebagian fisik bumi dengan menunjukkan penyebaran, ukuran dan bentuk dari kenampakan topografi.
Untuk mengenal kenampakan alam atau bentang alam pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 dasar elemen pengenalan, yaitu Kontur, Relief, Pola dan hubungan dengan kenampakan sekitarnya, Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut seseorang dapat memperkirakan bentuk permukaan dari bumi lebih lanjut lagi orang dapat memprediksikan bentuk medan yang akan dihadapi.
Klasifikasi Jenis Peta
Berdasarkan Jenisnya
- Peta Foto: dihasilkan dari mozaik foto udara atau ortofoto, dilengkapi garis kontur dan legenda.
- Peta Garis: menggambarkan detail buatan manusia dalam bentuk titik, garis, atau area (contoh: peta topografi dan peta tematik).
Berdasarkan Skala
- Peta skala besar: skala 1:25.000 hingga 1:50.000 (detail lebih tinggi).
- Peta skala kecil: skala lebih besar dari 1:50.000 (area cakupan lebih luas, detail lebih sedikit).
Berdasarkan Fungsi
- Peta Umum: menyajikan informasi lengkap dan umum (contoh: atlas, peta topografi).
- Peta Tematik: menyajikan informasi khusus (contoh: peta jaringan jalan).
- Chart (Peta Navigasi): digunakan untuk keperluan navigasi laut (nautical) dan udara (aeronautical).
Berdasarkan Topik atau Tujuan
Sering kali disamakan dengan peta tematik. Umumnya digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti peta geologi, peta cuaca, atau peta penduduk.
Perlu Diperhatikan dalam Membaca Peta Topografi
Kelengkapan peta sangat penting agar pengguna dapat memahami informasi geografis secara menyeluruh dan akurat. Elemen-elemen tersebut mencakup:
a. Indeks Peta
Indeks peta menunjukkan sistem grid yang membagi wilayah peta ke dalam kotak-kotak. Di Indonesia:
- Arah timur diberi angka: 1, 2, 3, …
- Arah selatan diberi angka Romawi: I, II, III, …
Contoh: 48/XLII-B artinya:
- 48: lokasi ke arah timur.
- XLII: lokasi ke arah selatan dari Sabang.
- B: salah satu bagian dari kotak tersebut (dari A, B, C, D).
Ukuran peta skala 1:50.000 biasanya berukuran 55 x 55 cm.
b. Judul Peta
Adalah identitas peta yang tergambar pada peta ditulis nama daerah atau identitas lain yang menonjol
c. Keterangan Pembuatan
Menjelaskan instansi pembuat, waktu pembuatan, serta sumber data. Dicantumkan di bagian kiri bawah peta.
d. Nomor Peta
Berfungsi sebagai kode unik untuk peta tersebut. Letaknya di sudut kanan atas peta.
e. Pembagian Lembar Peta
Penjelasan nomor-nomor peta lain yang tergambar disekitar peta yang digunakan bertujuan untuk memudahkan penggolongan peta bila memerlukan interpretasi suatu daerah yang lebih luas. Dicantumkan di sudut kanan kiri peta
f. Sistem Koordinat
Terdapat tiga jenis sistem koordinat pada peta topografi:
- Koordinat Geografis: Menggunakan garis lintang (LU/LS) dan garis bujur (BT/BB). Dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik.
- Koordinat Grid (UTM): Menggunakan sumbu X (absis) dan Y (ordinat) dalam satuan meter. Contoh:
- 72100 mE dibaca cukup “21”
- 99700 mN dibaca cukup “97”
- Koordinat Lokal: Digunakan ketika peta tidak memiliki grid resmi. Garis-garis dibuat secara manual, dan pengguna harus menyepakati sistem ini bersama-sama untuk menghindari kekeliruan. sistem koordinat yang dibuat secara manual atau tidak resmi, biasanya digunakan jika peta tidak mencantumkan koordinat grid (UTM) atau ketika pengguna ingin membuat sistem referensi sederhana di suatu area kecil dan tidak mengacu pada sistem internasional seperti UTM atau geografis (LU/LS, BT/BB), tapi hanya sebagai acuan internal.
g. Skala Peta
Skala menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di lapangan.
Rumus umum: Skala Peta=Jarak di Peta (JP)/Jarak di Medan (JM)
Keterangan:
- Skala Peta → tanpa satuan (misalnya: 1 : 25.000)
- JP → jarak pada peta (misalnya dalam cm atau mm)
- JM → jarak sebenarnya di lapangan (dalam satuan yang sama dengan JP, biasanya cm)
Tiga bentuk skala umum:
- Skala Numerik: Misalnya 1:25.000, 1:50.000
- Skala Grafik: Ditampilkan dalam bentuk garis berskala yang menggambarkan jarak sebenarnya
- Skala Verbal atau Perbandingan: Misalnya 1 inch = 1 mil
h. Orientasi Arah Utara
1. Utara Sebenarnya (True North / TN / US)
- Dilambangkan dengan simbol: ★ (bintang)
- Arah menuju kutub utara geografis
- Ditentukan berdasarkan rotasi bumi dan peta dunia
2. Utara Peta (Grid North/ GN / UP)
- Dilambangkan dengan: GN
- Sejajar dengan garis grid (sumbu Y) pada peta
- Digunakan sebagai acuan dalam sistem koordinat grid
3. Utara Magnetis (Magnetic North / MN / UM)
- Dilambangkan dengan: setengah anak panah (↖)
- Ditunjukkan oleh jarum kompas
- Tidak tetap, karena arah magnetis bumi berubah setiap tahun
- Perubahan ini disebut variasi magnetis (VM)
Penyimpangan Arah (Sudut Perbedaan Utara)
Karena ketiga arah utara tersebut tidak berada pada satu garis, maka akan terjadi penyimpangan sudut. Ini penting untuk diperhitungkan dalam navigasi:
Ikhtilaf Peta (IP)
- Sudut antara Utara Sebenarnya (US) dan Utara Peta (UP)
- Disebut juga konvergensi meridian
Ikhtilaf Magnetis (IM)
- Sudut antara Utara Sebenarnya (US) dan Utara Magnetis (UM)
- Disebut juga deklinasi magnetis
Sudut Peta Magnet (SPM)
- Sudut antara Utara Peta (UP) dan Utara Magnetis (UM)
- Disebut juga deviasi, biasa ditulis di peta sebagai GM Angle
Orientasi Arah
Sudut Kompas
Sudut antara Utara Magnetis (MN) dan arah sasaran yang dibidik melalui kompas
Sudut Peta
Sudut antara Utara Peta (GN) dan arah sasaran yang dituju pada peta
Garis Kontur
Garis kontur adalah garis khayal pada peta topografi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Garis ini digunakan untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi.
Sifat-sifat Garis Kontur:
- Garis kontur selalu merupakan kurve tertutup sejajar dan tidak akan memotong satu sama lain, kecuali pada daerah overhanging clift.
- Garis kontur yang didalam selalu lebih tinggi disbanding yang diluar.
- Interval kontur selalu merupakan kelipatan sama.
- Garis kontur selalu bersifat horizontal
- Garis kontur tidak pernah bertemu dengan garis kontur lain yan gberbeda indeks konturnya.
- Garis kontur yan grapat akan menggambarkan medan yan gterjal, sedang yang renggang menggambarkan medan yang landai.
- Pada lembah, garis kontur meruncing kearah hulu
- Garis kontur selalu tegak lurus arah aliranyang mengalir di permukaan, misalnya sungai.
- Garis kontur indeks diambarkan lebih tebal daripada garis kontur lainnya.
Fungsi Garis Kontur dalam Pemetaan:
- Menunjukkan ketinggian dan beda tinggi suatu tempat.
- Menunjukkan bentuk lereng
- Menunjukkan kemiringan lereng
- Pola kontur juga dapat untuk menentukan relief medan
Kompas
Kompas adalah alat bantu navigasi yang digunakan untuk:
- ✅ Menentukan arah
- ✅ Mengukur sudut datar terhadap arah utara magnetik
Jarum kompas bekerja dengan prinsip medan magnet bumi. Ia selalu mengarah ke kutub utara magnetik, dan arah ini dikenal sebagai Utara Magnet (UM). Sementara itu, Sudut Kompas (SK) adalah sudut antara arah utara magnetik dengan garis sasaran yang dibidik.
Kerja Kompas
Kompas menggunakan sistem skala 360° yang disebut azimuth, yang artinya:
- Utara = 0°
- Timur = 90°
- Selatan = 180°
- Barat = 270°
Penulisan arah biasa dikombinasikan dengan notasi huruf seperti berikut:
| Arah | Notasi Azimuth |
|---|---|
| Timur | N90°E |
| Barat | N270°E |
| Selatan | N180°E |
Jadi, arah timur adalah 90° dari arah utara, arah barat adalah 270°, dan seterusnya.
Jenis Kompas Berdasarkan Fungsi
1. Kompas Geologi
- Digunakan untuk survei geologi.
- Selain menunjukkan arah, dapat mengukur kemiringan lapisan batuan atau lereng.
2. Kompas Prisma (Kompas Bidik)
- Umum dipakai dalam militer.
- Keunggulannya:
- Praktis untuk pembacaan
- Jarum stabil dan cepat menunjukkan arah
- Memungkinkan bidikan langsung ke objek
3. Kompas Silva (Kompas Jalan)
- Ideal untuk penjelajahan, mendaki gunung, dan orientasi medan.
- Keistimewaan:
- Ringan, kuat, dan transparan
- Dapat digunakan sebagai penggaris dan busur derajat
- Praktis untuk plotting di peta topografi
Bagian-Bagian Kompas
komponen-komponen kompas di dalamnya antara lain:
- Dial. Permukaan berbentuk lingkaran dengan angka derajat dan arah mata angin.
- Visir. Celah kecil atau kawat halus untuk membidik sasaran arah.
- Kaca Pembesar. Untuk melihat angka derajat kompas dengan jelas.
- Jarum Penunjuk. Menunjukkan arah utara magnet bumi.
- Tutup Dial. Dapat diputar dan terdapat dua garis bersudut 45° untuk membantu penyelarasan.
- Alat Penyangkut. Penopang ibu jari untuk kenyamanan saat membidik arah.
Cara Menggunakan Kompas
- Letakkan kompas pada permukaan datar
- Tunggu hingga jarum diam, dan perhatikan arah utara magnetik.
- Membidik Sasaran
- Gunakan visir untuk membidik arah tujuan.
- Miringkan kaca pembesar sekitar 50° terhadap dial untuk membaca angka derajat arah.
- Bantu Bidikan dengan Tutup Dial
- Jika visir kurang jelas, sejajarkan garis pada tutup dial ke arah sasaran agar lebih mudah dilihat.
- Tentukan Arah dan Objek Sasaran
- Contoh: Jika arah sasaran adalah 30°, cari objek mencolok di arah 30°, seperti pohon besar atau batu menonjol.
- Perhatikan medan
- Jika rute penuh rintangan (seperti rawa), lakukan melambung sambil tetap menjaga arah ke objek sasaran.
- Tentukan Sasaran Balik (Back Azimuth)
- Penting untuk kembali ke pangkalan jika tersesat.
Rumus Back Azimuth (Sasaran Balik)
| Kondisi | Rumus |
|---|---|
| Derajat < 180° | Derajat + 180° |
| Derajat ≥ 180° | Derajat – 180° |
Contoh:
- Sasaran 30° → Back Azimuth = 30° + 180° = 210°
- Sasaran 240° → Back Azimuth = 240° – 180° = 60°
Arah Mata Angin
| Arah Mata Angin | Derajat |
|---|---|
| Utara (U) | 0° / 360° |
| Timur Laut (TL) | 45° |
| Timur (T) | 90° |
| Tenggara (TG) | 135° |
| Selatan (S) | 180° |
| Barat Daya (BD) | 225° |
| Barat (B) | 270° |
| Barat Laut (BL) | 315° |
Menentukan Arah Tanpa Kompas
- Makam Muslim: Umumnya menghadap kiblat (barat di Indonesia).
- Masjid: Arah mihrab menghadap barat (arah kiblat).
- Matahari dan Bulan: Terbit di timur, terbenam di barat.
- Lumut pada Pohon: Lebih banyak tumbuh di sisi selatan (lembab).
- Ujung Daun: Cenderung tumbuh ke arah cahaya (timur).
- Menggunakan Silet atau Jarum: Bisa digunakan sebagai kompas darurat jika dialiri medan magnet.
Sebelum Menggunakan Kompas
Menyetel Kompas
Sebelum digunakan, semua kompas yang akan dipakai harus diseragamkan dengan kompas standar. Cara termudah melakukan pengecekan adalah pergi ke titik Triangulasi yang sudah diketahui Sudut Peta Medannya (SPM), misalnya 0° 00′ 00″. Lalu, plot tanda medan yang jelas terlihat dari titik Triangulasi dan juga ada di peta. Catat sudut petanya, misalnya 50°. Jika kompas yang Anda gunakan sudah disetel dengan benar, maka sudut hasil bidikan ke tanda medan itu dari titik Triangulasi harus sama, yaitu 50° juga.
Periksa Skala Derajat Kompas
Perhatikan pembagian derajat pada piringan kompas. Disarankan menggunakan kompas dengan skala 0°–360°, karena lebih umum dan praktis. Jika Anda menggunakan kompas dengan skala 6400 mil, maka Anda harus mengonversi nilainya terlebih dahulu saat membaca peta atau menentukan azimut di lapangan.
Orientasi
Orientasi Peta:
- Cari tempat terbuka, agar tanda medan terlihat jelas.
- Letakkan peta di permukaan datar.
- Gunakan kompas, pastikan sudutnya 0° atau 360°, lalu sejajarkan dengan garis sumbu Y peta.
- Putar peta (bukan kompasnya) hingga garis sumbu peta sejajar dengan arah utara kompas.
- Cocokkan tanda medan nyata dengan peta, lalu beri tanda.
- Temukan sebanyak mungkin tanda medan untuk memahami wilayah dan memperkirakan posisi Anda.
Orientasi Medan dengan Kompas
a. Resection (Menentukan Posisi Kita)
Langkah-langkah:
- Identifikasi tanda medan yang jelas (puncak bukit, sungai, tebing, dll).
- Bidik tanda medan menggunakan kompas dari posisi Anda.
- Catat sudut kompas. Misalnya: Bukit X = 130°.
- Hitung sudut peta: Azimut Peta = 130° + 180° = 310°.
- Gunakan busur dan penggaris untuk menggambar garis dari titik tanda medan ke arah 310°.
- Ulangi langkah ini untuk tanda medan kedua.
- Titik perpotongan dua garis adalah posisi Anda di peta.
b. Intersection (Menentukan Posisi Objek Lain)
Langkah-langkah:
- Berdiri di titik yang sudah diketahui (misalnya titik X di peta).
- Bidik objek (misalnya tenda, bukit, atau orang lain).
- Catat sudut kompas. Misalnya: 130°.
- Gambar garis dari titik X dengan azimut 130°.
- Pindah ke titik kedua (Y), ulangi proses yang sama.
- Titik perpotongan dua garis menunjukkan posisi objek yang dibidik.
Idealnya, perbedaan sudut antara titik X dan Y adalah antara 30°–150°. Intersection juga bisa dilakukan dari satu titik bila objek berada di lokasi tertentu seperti tepi sungai atau garis pantai.
Orientasi Medan Tanpa Peta dan Kompas
a. Matahari
- Berguna pada siang hari.
- Matahari terbit di timur dan terbenam di barat.
b. Bintang
- Bintang Pari (Crux) menunjukkan arah selatan.
- Bintang Orion dapat digunakan untuk mengenali timur–barat.
c. Tanda-tanda Lingkungan
- Kuburan umat Islam biasanya membujur utara–selatan.
- Masjid menghadap ke arah barat (arah kiblat).
Teknik Passing Kompas
Passing kompas adalah metode navigasi yang biasa digunakan saat menghadapi rintangan di medan, seperti sungai, jurang, hutan lebat, atau daerah yang tidak bisa dilalui langsung. Teknik ini sangat efektif pada medan datar dan terbuka, serta dapat dilakukan dengan koordinasi tim yang baik.
Langkah-langkah Passing Kompas:
- Tentukan Titik Tujuan
Identifikasi lokasi tujuan pada peta sebelum perjalanan dimulai. - Hitung Sudut Arah (Azimut)
Gunakan kompas untuk menentukan sudut azimut dari titik awal menuju titik tujuan di peta. Hitung juga back azimuth (arah sebaliknya), yang berguna bila harus kembali ke titik semula. - Pionir ke Titik Pandangan
Minta 1–2 orang rekan bergerak ke depan sesuai arah bidikan kompas sejauh pandangan mata masih memungkinkan. - Lanjutkan Pergerakan Secara Bergantian
Setelah rekan sampai pada titik bidik, Anda maju ke posisi mereka, kemudian lakukan kembali bidikan kompas ke arah yang sama. Ulangi proses ini hingga mencapai tujuan. - Pastikan Posisi Kompas Akurat
Setiap bidikan harus dilakukan dengan jarum kompas sejajar Utara–Selatan (N–S) agar arah tetap akurat.
Kalibrasi Kompas
Kompas, meskipun terlihat seragam, bisa menunjukkan perbedaan kecil dalam sudut bacaan karena faktor usia, kualitas, atau gangguan medan magnet. Untuk itu, dilakukan proses kalibrasi, yaitu menyamakan pembacaan antara kompas yang digunakan dengan kompas standar.
Contoh Kalibrasi:
Misalnya, Anda memiliki kompas A, kompas B, dan kompas C sebagai kompas standar. Objek bidikan adalah Bukit X.
Langkah-langkah:
- Bidik dengan Kompas C (Standar)
Hasil sudut azimut: 45° - Bidik dengan Kompas A dan B ke objek yang sama
- Kompas A: 47°
- Kompas B: 42°
- Hitung Selisih Kalibrasi
- Kompas A → 47° – 45° = +2°
➜ Maka, saat menggunakan kompas A di lapangan, hasil bidik harus dikurangi 2°. - Kompas B → 45° – 42° = +3°
➜ Maka, saat menggunakan kompas B, hasil bidik harus dikurangi 3°. - Dengan begitu, arah dan sudut bidikan dari semua kompas akan seragam sesuai standar yang telah ditetapkan.
- Kompas A → 47° – 45° = +2°
Hindari Gangguan Magnetik
Agar hasil bidikan kompas tidak menyimpang, hindari melakukan kalibrasi atau pembidikan kompas di dekat benda-benda logam atau sumber medan magnet, seperti:
| Benda atau Objek | Jarak Aman Minimal |
|---|---|
| Senjata berat | 60 meter |
| Senjata ringan | 40 meter |
| Pagar kawat | 10 meter |
| Parang, pisau, logam kecil | 3 meter atau lebih |
Unduh aplikasi yang akan mempermudah anda dalam bernavigasi dengan mudah dimedan maupun menggunakan peta secara akurat dan tentunya dengan ketelitian.
Baca juga:
Berikut adalah link download langsung dari Google Play Store untuk dua aplikasi Anda:
- Aplikasi Arah dan Jarak
🔗 Download di Google Play Store - Aplikasi Kalkulator Koordinat (Calc Coordinate)
🔗 Download di Google Play Store